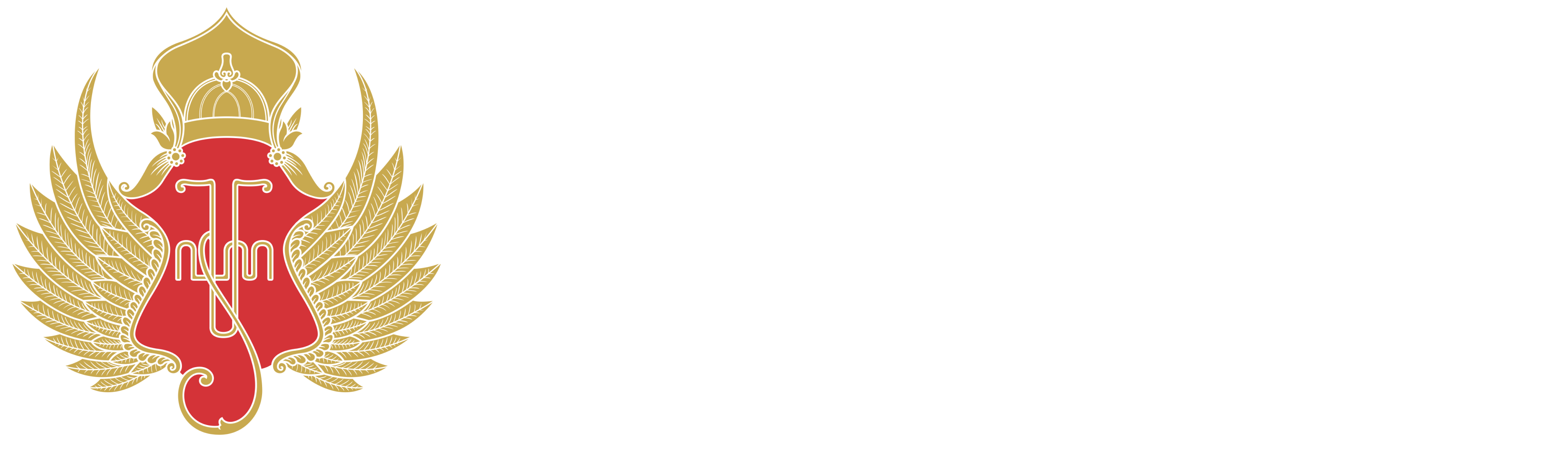Mas Wedana Perwitowiguno, Totalitas Empu Wayang Kulit Gaya Yogyakarta
- 22-02-2022

November 2003, wayang kulit ditetapkan UNESCO sebagai Adikarya Warisan Budaya Tutur dan Takbenda. Walau wayang kulit kini tak sepopuler dahulu, karya seni nan luhur ini tetap bertahan dan memiliki banyak penggemar. Kelestariannya tak luput dari ketekunan para seniman yang terus merawat keberadaan wayang kulit. Pak Sagio, empu wayang gaya Yogyakarta, merupakan salah satunya.
Desa Gendeng, Bangunjiwo, tempat Sagio lahir, merupakan salah satu sentra kerajinan tatah sungging kulit di Yogyakarta. Semasa kecil, Pak Sagio sering melihat pertunjukan wayang dan ketoprak yang merupakan hiburan lazim pada masa itu. “Di kampung itu kan satu-satunya kesenian itu wayang kulit dan ketoprak. Lainnya belum ada. Jadi sambil angon wedhus (menggembala kambing) saya membuat wayang tetapi dari daun singkong. Dianyam,” kenangnya.
Ketertarikan Sagio kepada wayang kulit tak lepas dari pengaruh ayahnya, Jaya Perwita, yang bekerja sebagai penatah wayang kulit. Sagio mulai senang menggambar wayang sejak belia. Ia menyebutkan pada usia sebelas sebagai titik mulanya belajar wayang secara serius. Setelah berguru pada sang ayah, ia kemudian belajar lebih mendalam di bawah bimbingan empu-empu wayang kulit, seperti Puja Winata, pemahat wayang dari Desa Gendeng, dan MB Prayitno Wiguno, Abdi Dalem keraton.
Meski Sagio sudah sangat terampil, ia merasa ilmunya belum cukup. Tahun 1978, Pak Sagio melamar posisi Abdi Dalem, saat itu ia merasa sedih sekaligus kecewa karena guru memahatnya meninggal dunia. “Untuk ngangsu kawruh lagi. Satu-satunya jalan (mencari ilmu) saya harus masuk keraton untuk melihat wayang yang sudah ada,” tuturnya mengenai tujuannya bergabung dengan keraton. “Pokoknya saya ingin menjadi Abdi Dalem agar bisa nonton wayang kulit. Kan tidak semua orang bisa nonton koleksi keraton.”
Setelah magang empat tahun, Pak Sagio diwisuda menjadi Abdi Dalem dan menerima nama Paring Dalem Perwitowiguno oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pak Sagio masuk dalam golongan Abdi Dalem Natah Sungging di KHP Kridhamardawa. Lebih dari empat puluh tahun mengabdi, kini Pak Sagio berpangkat Wedana. Namun, pangkat dan materi tak begitu ia hiraukan. Baginya yang terpenting adalah bisa menggeluti wayang dan memang menjadi panggilan jiwanya. “Awalnya tujuan saya ke sini itu nonton wayang dan bisa menjadi Abdi Dalem. Saya tidak ada niatan pengin dapat pangkat ini dan itu. Boleh nonton wayang itu sudah alhamdulillah sekali.”

Perawat Wayang dan Aksesori Busana Tari
Keraton memiliki kurang lebih dua ribu buah wayang kulit yang sebagian sudah sangat tua. Perawatan benda-benda berharga itu menjadi tugas utama Mas Wedana (MW) Perwitowiguno. “(Tugas saya) merawat dan memperbaiki kalau ada yang rusak, talinya putus, atau sobek, atau warnanya hilang. Kan ada wayang yang karena lama, sobek. Itu bagian saya. Tugas saya.”
Tugas tersebut membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian tinggi. Kerusakan ringan bisa diperbaiki dalam waktu sehari, sementara yang berat, misalnya sobek, bisa memakan waktu seminggu.
Perawatan pelengkap kostum pertunjukan tari dan Wayang Wong yang terbuat dari kulit juga merupakan tanggung jawabnya. Tak sekadar merawat, Mas Wedana Perwitowiguno juga membuat aksesori-aksesori yang dibutuhkan, seperti kelat bahu dan mahkota.
Tugas lain yang tak kalah penting adalah merawat dan merenovasi tempat duduk kereta kencana. “Saya pernah renovasi kereta kencana, membuat tempat duduk kusir. Itu (memakan waktu) dua tahun lho,” ujarnya.
Kepedulian pada Pendidikan
Saat ini ada empat juru tatah dan sungging di bawah KHP Kridhamardhawa, “Yang masih muda ada tiga, itu (seusia) adik-adik saya. Saya yang paling tua.” Seminggu dua kali ada Abdi Dalem yang datang ke keraton untuk melaksanakan tugas.
MW Perwitowiguno mengakui regenerasi juru tatah dan sungging bukan perkara mudah. Namun, ia bersyukur kini sudah ada lembaga pendidikan formal untuk mengajarkan keterampilan ini. “Atas inisiatif Sri Sultan Hamengku Buwono X, supaya wayang kulit masih bisa lestari, dibuat sekolah khusus buat wayang kulit di Akademi Komunitas Negeri.” Di akademi tersebut, MW Perwitowiguno menjadi salah satu pengajar.
Jauh sebelum lembaga pendidikan itu dibuka, MW Perwitowiguno sudah bergerak melatih talenta-talenta muda penerus kesenian tradisi ini. Pak Sagio mendirikan “Griya Ukir Kulit” workshop dan toko wayang yang berada di rumahnya di Desa Gendeng, Bangunjiwo. Pak Sagio membuka galeri itu sebagai perguruan bagi siapa pun yang ingin belajar membuat wayang kulit. Ia melatih para pemuda yang tertarik tanpa memungut biaya. “Dahulu banyak anak muda yang nganggur, sekitar tahun 70 saya tarik untuk belajar. Dari tahun 1971-1997 sudah ada lima puluh anak. Pokoknya dari swadaya saya. Artinya semua kebutuhan mereka itu saya yang nyukupi, alat, bahan, makan dan (mereka) tidak membayar. Tujuan saya hanya supaya kampung saya jadi kampung wayang.”
Tak hanya pemuda setempat yang ia didik, namun juga mahasiswa seni dan warga negara asing. “Banyak orang asing yang ikut belajar, walaupun hanya satu hari, dua jam. Bisa,” katanya terkait ekspatriat yang datang ke workshop-nya untuk belajar membuat wayang.
Sejalan dengan tekadnya untuk melestarikan kesenian peninggalan nenek moyang ini, Pak Sagio juga menulis buku tentang wayang. Empat judul sudah diterbitkan, salah satunya, “Wayang Kulit Gaya Yogyakarta, Morfologi Tatahan dan Sunggingan.” Buku yang lain berjudul “Wayang Kulit: Bentuk dan Cerita.” Buku ini menjadi bahan ajar di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta.
Cinta
Mungkin hanya “cinta” yang bisa menjelaskan totalitas bapak tiga anak ini dalam melestarikan wayang. Nyaris seluruh hidupnya didedikasikan untuk wayang dan kriya kulit pada umumnya. Ia membuat, menjual, dan mengerjakan pesanan wayang dan aksesori tari dari perseorangan maupun komunitas. Semuanya dalam gaya khas Yogyakarta.
Tidak main-main, karyanya pernah rutin dikirim ke Istana Negara untuk dijadikan suvenir bagi tamu-tamu negara pada era Presiden Soeharto. Tak terhitung lagi wayang buatannya yang sudah merambah mancanegara.
“Banyak pesanan dari sanggar-sanggar itu. Yang saya buat itu khusus gaya Yogyakarta yang di pasaran tidak ada.”
Saat sedang butuh bersenang-senang, Pak Sagio lagi-lagi berkreasi dengan tema wayang. Ia membuat beragam lukisan wayang dengan aneka media seperti kulit, kaca, kulit, kertas, kanvas. Cinta membuatnya terus melaju nyaris tanpa bosan, “Tidak pernah bosan. Kalau lagi kalut itu malah menggambar. Itu untuk menghibur diri. Itu kan merupakan hiburan. Jadi bukan saya membuat ini supaya laku. Saya menuruti senangnya hati.”
Di waktu senggang, sumber kesenangannya lagi-lagi berkisar pada wayang, “Nonton wayang. Mendengarkan (siaran pertunjukan) wayang dari radio. Sekarang ada (tontonan wayang) YouTube.”
Bertahun-tahun menggeluti seni kerajinan kulit, Pak Sagio sadar betul hanya mereka yang sungguh-sungguh berangkat dari kecintaanlah yang akan bertahan. “Membuat wayang kalau tidak didasari rasa senang, itu biasanya bosan.”

Duta Budaya
Keahliannya yang unik telah membawa MW Perwitowiguno keliling dunia. Benua Amerika, Eropa, dan Asia telah dijelajahinya. MW Perwitowiguno ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menggawangi pameran-pameran budaya di berbagai negara dan seringkali disertai sesi pelatihan untuk warga yang tertarik belajar. “Orang asing saja kalau belajar antusias sekali. Saya pernah diminta mengajar workshop di Amerika. Itu orang pada antre sampai nggak kebagian tempat duduk.”
Sementara di wilayah tempat tinggalnya, penerima penghargaan seni dari Pemerintah DIY dan penghargaan Upakarti dari Presiden (1990) untuk kategori jasa pengabdian ini aktif dalam komunitas seni “Kaji Gelem”. Komunitas tersebut merupakan singkatan nama kampung-kampung seni di Kelurahan Bangunjiwo yaitu Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi.
Keberuntungan Besar
Pengabdian di keraton dianggap sebagai berkah oleh MW Perwitowiguno. Selain bisa melihat wayang koleksi keraton secara langsung, ia merasa beruntung karena bisa menjalani tugas-tugas luar biasa, misalnya mengganti kelambu di Gedhong Prabayeksa yang hanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Juga memasang kelambu di makam Sultan Agung. “Itu kan keberuntungan saya. Itu karena saya jadi Abdi Dalem di sini.”
Pak Sagio juga merasa hidupnya lebih tenang setelah mengabdi di keraton karena pengaruh unggah-ungguh yang diterapkan di keraton. “Semeleh-nya itu iya, tidak kemrungsung. Karena di sini semuanya begitu. Tidak boleh tergesa-gesa. Peraturannya begitu.”
Tak ada lagi ambisi besar untuk dirinya sendiri. Harapan ia gantungkan untuk generasi penerus, termasuk anak bungsunya kini kuliah di Jurusan Kriya Kulit ISI Yogyakarta dan sering membantunya berkarya.
MW Perwitowiguno memaklumi perubahan teknologi dan pergeseran selera anak muda menjadi tantangan besar, tetapi ia optimistis selalu ada anak-anak yang akan tumbuh mencintai wayang. Yang terus ia lakukan adalah merawat minat-minat itu. “Saya senang menularkan pengetahuan, biar panjang umurnya.” Pak Sagio juga berharap budaya keraton tetap lestari karena hal itu menjadi pedoman dan barometer bagi rakyat di Yogyakarta.