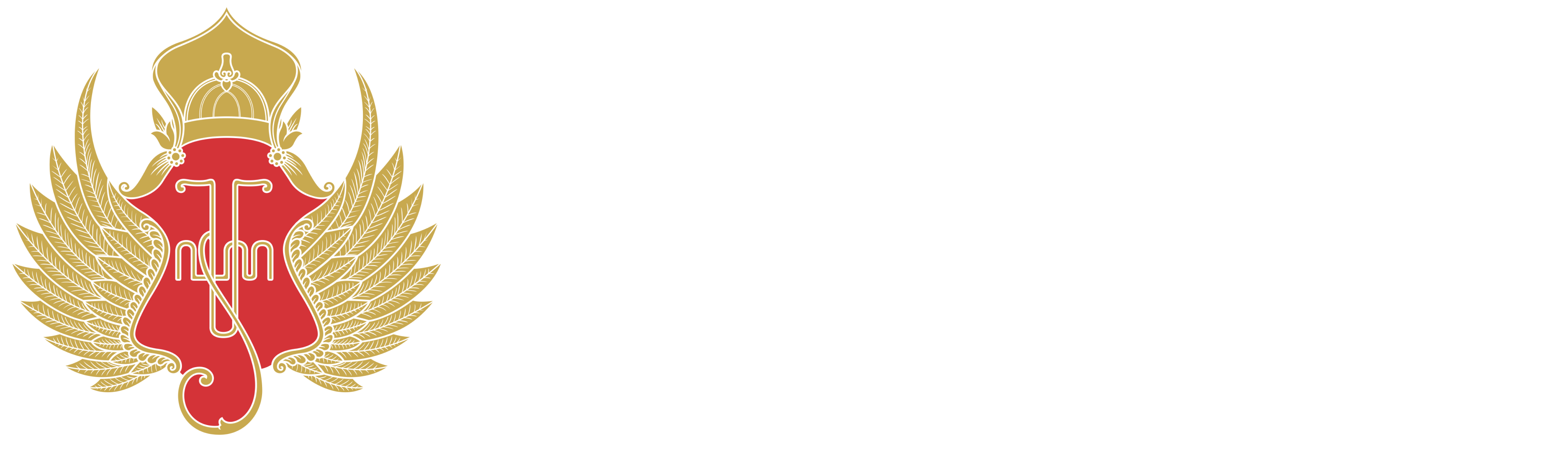Sigit Nurwanto, Lampah Macak Peniup Seruling Nyutra
- 23-09-2024

Sigit Nurwanto tak pernah membayangkan bisa menjadi bagian keluarga besar Keraton Yogyakarta. Ia berasal dari Siraman, sebuah desa di Wonosari, Gunungkidul yang jauhnya puluhan kilometer dari pusat kota. Selain itu, ia tak mengerti apa-apa mengenai keraton, berkunjung pun belum pernah. Ia juga bukan keturunan Abdi Dalem atau kerabat keraton.
Namun, perjalanan akhirnya mempertemukannya dengan keraton tanpa ia rencanakan.

“Ceritanya saya dulu itu cuma ngantar teman,” tuturnya mengawali kisah. Teman tersebut anggota Bregada Nyutra yang bertugas sebagai ungel-ungelan (pemain musik). Setiap Minggu sore, bertepatan dengan jadwal latihan keprajuritan sang teman, mereka berdua naik sepeda menuju Malioboro dan keraton.
Mulanya, Sigit mengiyakan ajakan temannya semata untuk mengisi hari libur. Dua tiga kali ia melihat temannya tersebut berlatih hingga suatu ketika pengirit ungel-ungelan berkata, “Mbok temanmu itu jangan hanya duduk-duduk agak jauh, suruh ke sini.” Akhirnya Sigit duduk bergabung bersama anggota bregada yang sedang berlatih. “Saya yang tidak paham apa pun. Dikasih alat, seruling.” Sang pengirit berpesan agar Sigit membawanya pulang bersama notasi yang diberikan lalu mencobanya. “Siapa tahu kamu bisa,” katanya.
Sigit benar-benar mencoba. Ia belajar dari prajurit lain di Pracimasana (tempat latihan prajurit waktu itu). Itulah pengalaman pertama Sigit bersentuhan dengan seruling. Ia pun kesulitan pada mulanya, apalagi ia juga harus mempelajari kedua pola jalan bregada yakni lampah macak (indah) maupun lampah mares (gesit).
Awalnya, ia belajar memainkan gendhing prajurit sambil duduk. Masalahnya, begitu meniup seruling sambil berjalan, ia mendadak kesulitan. “Kalau langkah saya benar, (permainan) seruling saya keliru. Kalau main serulingnya lancar, langkah saya keliru.”
Namun, berkat latihan keras dan sikap pantang menyerah, Sigit akhirnya diterima magang. Tak sampai tiga bulan magang, ia sudah mendapat penugasan pertama, yaitu mengawal gunungan Garebeg Mulud 2009. “Alhamdulillah (saya) diterima sowan di Keraton Yogyakarta ini menjadi prajurit Nyutra, yang ditugaskan untuk nyuling atau korps musik.”
Tiap-tiap bregada memiliki satuan musik yang memainkan mars pengiring yang berbeda, walau jenis alat musiknya relatif sama. Korps musik Bregada Nyutra terdiri dari dua pemain seruling, dua penambur, dan dua pemain terompet.
Seruling yang dipakai oleh bregada berbahan aluminium dan dibuat khusus. “Kalau seruling yang saya pakai selama ini buatan teman Mantrijero yang senior. Jadi beliau paham, laras Bregada Nyutra, laras Bregada Wirabraja itu kadang tidak sama,” Sigit menjelaskan.
Terkait penampilan perdananya, Sigit mengingat saat itu pemain seruling senior Bregada Nyutra, Mbah Suraksa Supono, sama sekali tidak memainkan alat musiknya dari awal sampai akhir. “Dia mengetes saya, kuat atau tidak bila harus bermain sendiri.”

Mencintai Kesenian Jawa sejak Kanak-Kanak
Sebenarnya tidak mengherankan apabila Sigit tak butuh waktu lama untuk menikmati peran barunya sebagai anggota bregada. Menilik ke belakang, ia menggandrungi kesenian Jawa sejak kecil. Ia akui hobinya tersebut terbilang unik, “Mungkin berbeda dengan teman-teman sebaya saya yang waktu itu yang suka dangdut, band-band-an atau musik-musik pop yang lain. Sedangkan saya rada nyleneh. Dari teman-teman itu hanya saya sendiri yang justru suka melihat karawitan, ketoprak, wayang wong.”
Saking sukanya pada wayang, ia mantap merantau ke Yogyakarta selepas SMP dan belajar seni pedalangan di Sekolah Pedalangan Habirandha. Selain belajar, ia juga bekerja sebagai pembuat stempel di perusahaan desain grafis di bilangan Jetis Pasiraman. Keterampilan membuat stempel ia pelajari langsung di tempat kerja. Di tempat kerja itulah ia berkenalan dengan teman yang mengenalkannya ke keraton seperti yang telah diceritakan.
Seni keprajuritan tak pelak memesonanya. “Sangat menarik untuk saya yang warga Gunungkidul. Saya sangat jarang menemui kesenian keprajuritan dan saya juga sangat penasaran dengan kegiatan di keraton, kok orang-orang bisa menjadi Abdi Dalem, orang-orang kok memakai busana Jawa yang dulu itu sangat saya kagumi.”
Pada masa itu, Sigit terkadang tampil memainkan wayang di toko-toko atau pusat wisata. “Konsepnya ngamen. Iringannya gamelan biasa, ada playon-playon-nya, ada lancaran-nya. Pemainnya sekitar delapan sampai sepuluh orang, yang penting pertunjukan wayangnya berjalan.”
Setelah lulus dari sekolah pedalangan, Sigit yang merupakan anak tunggal ini kembali tinggal di Wonosari, Gunungkidul bersama kedua orang tuanya. Di sana ia mengembangkan pertunjukan wayang bersama teman-temannya.
Mereka membuat pertunjukan wayang yang dipadatkan dengan gamelan yang tidak terlalu banyak. Pertunjukan pun digelar di tempat-tempat unuk, seperti di bawah pohon beringin, di sumber mata air, atau di bawah dapuran bambu. “Sasarannya memberikan hiburan kepada teman-teman di sekitar karena berproses bersama itu kan menyenangkan sekali.”
Mereka juga sering diundang tampil untuk mengisi acara. Undangan ini acapkali datang mendadak, “Unsur dadakannya tinggi banget. Jadi saya sama teman-teman Gunungkidul itu ada kesempatan sambar, ada kesempatan sambar. Kadang-kadang mempersiapkan pertunjukan wayang itu dua hari tiga hari dengan lakon yang secuil saja, tidak usah panjang-panjang.” Dapat dibilang, Sigit dan teman-teman membawakan seni wayang kontemporer.
Selain nguri-nguri seni pewayangan, komunitas ini juga menyediakan layanan jamasan pusaka (perawatan senjata tradisional kategori tosan aji). Mereka menawarkan pada penduduk desa yang memiliki tosan aji untuk melakukan jamasan bersama. Pemilik bisa menitipkan pusaka milik mereka untuk dibersihkan untuk dikembalikan lagi setelah bersih. “Sudah berjalan tiga empat Sura ini lah,” jelas Sigit.
Pecinta Lingkungan dan Tempat-Tempat Bersejarah
Sehari-hari, Sigit bekerja sebagai karyawan di pangkalan gas LPG. Ia mengangkut dan mendistribusikan tabung-tabung gas ke warung-warung. Tentu saja, ia harus pandai mengatur waktu agar pekerjaan dan kewajiban di keraton dapat terlaksana dengan baik. Tak jarang ia berangkat pukul tiga pagi apabila bertugas mengawal Gunungan. “Saya kalau Garebeg kan jam 6 atau 6.30 harus siap di tempat.” Melaju seperti ini ia lakukan hanya apabila ia yakin dapat bangun pagi. Apabila tidak, ia memilih menginap di keraton, di rumah teman, atau di petilasan.
Untunglah, ia sudah memiliki kesepakatan dengan atasannya, “Dulu saya sudah matur sama pemiliknya kalau ada acara seni, saya tidak bisa meninggalkannya. Saya sudah matur sejak awal. Jadi mereka sudah paham.”
Selain mencintai seni tradisional, Sigit memiliki kepedulian tinggi pada kelestarian lingkungan. Kepedulian itu berawal dari matinya pohon beringin di dekat rumahnya. Pohon itu disinyalir diracun dengan rondap, padahal pohon tersebut merupakan patok atau penanda desa yang bersejarah. Bukannya marah atau mendendam, Sigit justru termotivasi untuk menanam lebih banyak beringin. Gerakan ini berlanjut. Sigit bersama teman-teman pengiring wayang menanam pohon di mana-mana saat musim hujan tiba. “Biasanya sasaran utamanya adalah Sultan Ground. Tanah-tanah milik sultan. Kami menaman pohon konservasi; pohon beringin, pohon kepuh, randu alas, dan lain-lain. Selain untuk menjaga mata air dan kesuburan tanah itu kan juga sangat diperlukan untuk menjaga kita dari kebencanaan. Itu yang sering saya dan teman-teman saya lakukan.”
Sebagian besar mereka dapatkan lewat memulung. Mereka mengambil pohon muda atau biji dari mana saja, kemudian dibawa pulang untuk disemai.
Ketika Keraton Yogyakarta menyelenggarakan pameran Narawandira 5 Maret - 29 Agustus 2023 yang bertemakan vegetasi istana, Sigit membantu menyediakan bibit pohon cabe jawa, kepel, dan lerak.
Di antara kesibukan mencari nafkah, mengabdi sebagai prajurit keraton, berkesenian, dan berkegiatan sosial, pemuda lajang ini menyempatkan diri untuk menyalurkan kegemarannya mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti makam dan petilasan. Nyaris semua petilasan di DIY sudah pernah ia sambangi, mulai dari Surcala, Gua Jepang, Wotgaleh, Tuk Si Bedug, hingga Ratu Malang.
Menata Perasaan
Lima belas tahun mengabdi di keraton, Sigit tentu mengalami senang dan susah. Ia mengaku harus menata perasaan saat diterima di keraton. Ia bahagia tergabung dalam kesatuan prajurit, tetapi juga sedih karena itu artinya ia tidak bisa sepenuhnya berkumpul dengan keluarga pada hari-hari besar seperti Idulfitri dan Iduladha sehubungan dengan tugasnya mengawal Gunungan Garebeg.
Ia juga kadang was-was saat bertugas piket dan pulang malam, “Pulang jam dua belas atau jam satu malam ke Gunungkidul, melewati hutan, kadang-kadang ada perasaan was-was. Nanti kalau disalip orang bawa senjata dan lain-lain.”
Namun, ia juga mendapat kebahagiaan dari jalinan persahabatan baru yang lebih luas di lingkungan keraton, “Misalnya butuh paraga untuk ngancani ndalang ringgit purwa, ada hubungan ke sana. Itu juga nilai plus.”
Merupakan suatu kebanggaan baginya dapat turut andil melestarikan budaya keraton. “Itu, sungguh luar biasa. Karena saya ini siapa, orang desa.” Salah satu pengalaman yang membuatnya terkesan adalah terlibat dalam ayahan Siraman Pusaka. “Saya gumun dan nggak nyangka saya diajak masuk Gedhong Pusaka. Itu juga sebuah kebanggaan.”
Sekolah Kehidupan
Bagi Sigit, menjadi prajurit di keraton adalah anugerah. Selain bisa dekat dengan budaya Jawa yang memang ia kagumi, ia mendapat banyak pelajaran dari sesepuh-sesepuh yang ia temui. Dari dialog-dialog dengan mereka, Sigit memetik banyak pelajaran berharga.
Meski sudah kaya pengalaman, Sigit tak berani memberi wejangan apa pun, “Saya kadang-kadang takut. Kalau menjadi dalang, itu (memberi petuah) saya hindari. (Takut) disangka sok pintar.”
Namun, ia tak pernah segan untuk mengajak siapa saja untuk peduli pada lingkungan termasuk mencintai pohon, “Karena di bawah pohon-pohon itu muncul kehidupan. Dari kehidupan itu muncul upacara adat yang memantik lahirnya kesenian-kesenian yang berkembang hingga sekarang ini. Semuanya berawal dari pohon kehidupan. Pesan saya, mari merawat pohon-pohon, merawat lingkunganmu, merawat pohon kehidupanmu dan pohon-pohon persaudaraan kita semua.”
Dengan kiprahnya saat ini, Sigit telah membawa kebanggaan khusus untuk kedua orang tuanya, meski kebanggaan itu tidak dilahirkan dalam kata-kata. “Mungkin mereka juga nggak menyangka, kamu itu anak siapa, kamu itu besar di mana, kok bisa diterima sowan ngabekti di keraton.” Dari kedua orang tuanya Sigit mendapatkan dukungan moral dan sebagai bagian dari bakti, ia mengajak keduanya untuk mengunjungi keraton yang belum pernah mereka tapaki sebelumnya.
“Doa saya untuk Keraton Yogyakarta semoga tetap lestari, ayom ayem seluruh rakyatnya, gemah ripah buminya, berkemakmuran seluruh rakyat Keraton Yogyakarta,” harapnya.