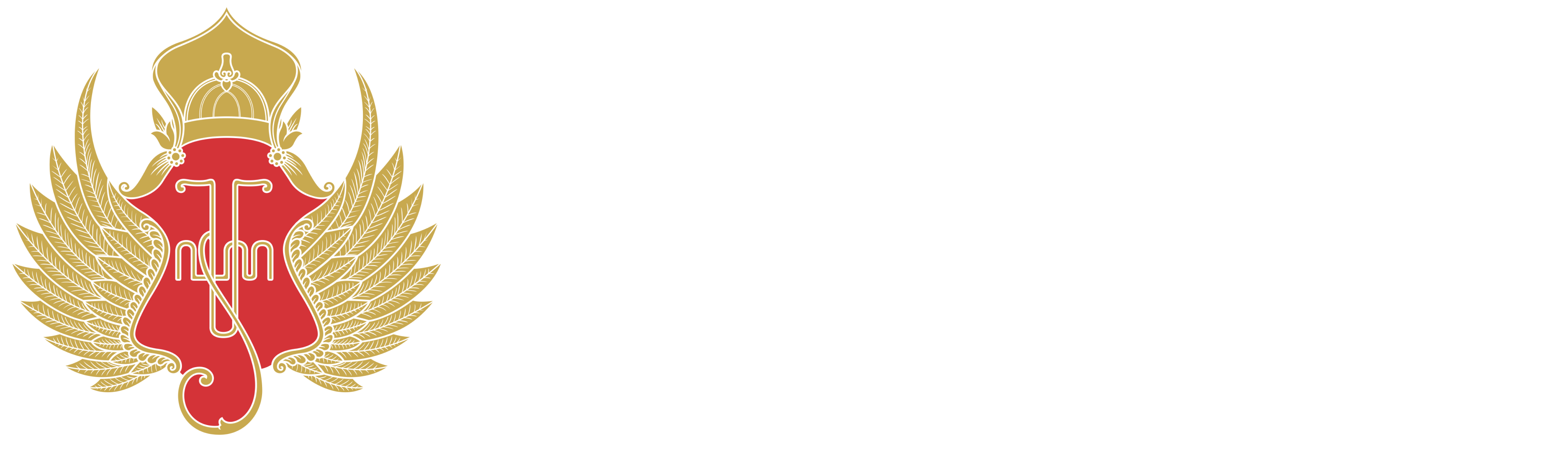Srimpi, Tari Klasik Gaya Yogyakarta
- 09-07-2019

Tari Srimpi sulit dipisahkan dari tari Bedhaya. Bahkan tari Bedhaya kerap disebut dengan istilah Srimpi Lajuran karena komposisi empat penari di luar lajur yang mengapit lima penari. Para penari yang membawakan Srimpi dan Bedhaya pun disebut dengan istilah yang sama, Bendara Bedhaya. Namun berbeda dengan Bedhaya, semua penari Srimpi memiliki peran yang sama. Keempat penari Srimpi ini melambangkan kiblat papat, atau empat arah mata angin.
Penamaan Tari Srimpi
Tari Srimpi pada umumnya disebut dengan nama gendhing pengiringnya, misalnya pada Srimpi Pandhelori mempergunakan Gendhing Pandhelori atau Srimpi Merak Kesimpir dengan iringan Gendhing Merak Kesimpir. Adapula Srimpi yang dinamai dengan nama cerita atau tema yang diungkapkan. Misalnya, Srimpi Renggawati yang mengisahkan Prabu Angling Darma saat menjelma menjadi burung meliwis putih untuk mencari titisan Dewi Renggawati. Meski diiringi dengan gendhing Renyep, Srimpi yang dibawakan oleh lima penari ini jarang dikenal dengan nama Srimpi Renyep.
Kisah atau tema tari Srimpi banyak diilhami dari berbagai cerita, termasuk kisah Mahabharata dan Serat Menak. Misalnya Srimpi Pandhelori yang mengisahkan pertarungan antara Dewi Sudarawerti dengan Dewi Sirtupelaeli, atau Srimpi Muncar yang menceritakan pertarungan antara Dewi Kelaswara dengan Dewi Adaninggar saat memperebutkan Wong Agung Jayengrana. Cerita dalam Srimpi dibawakan dalam bentuk Gerongan, lagu yang dibawakan oleh pesindhen untuk menghidupkan jalannya cerita.

Srimpi Renggawati di Bangsal Srimanganti
Perkembangan Tari Srimpi
Srimpi di Keraton Yogyakarta berkembang pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono V (1823-1855). Setidaknya tiga tari Srimpi lahir pada masa itu: Srimpi Renggawati, Srimpi Kandha, dan Srimpi Ringgit Munggeng Kelir. Adapun penciptaan Srimpi Kandha dan Srimpi Ringgit Munggeng Kelir dipengaruhi oleh bentuk wayang kulit yang saat itu sedang berkembang dengan pesat. Selanjutnya Srimpi Pandhelori, Srimpi Pistol, Srimpi Pramugari, Srimpi Merak Kesimpir, Srimpi Endra Wasesa dan Srimpi Dhendang Sumbawa tercipta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877) dan Sri Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921).
Tari Srimpi awalnya tumbuh dan diajarkan di dalam lingkup tembok keraton sehingga hanya dikuasai kalangan kerabat Sultan atau Abdi Dalem. Baru pada tahun 1918, seiring dengan didirikannya sanggar Kridha beksa Wirama oleh putra Sri Sultan Hamengku Buwana VII, tari Srimpi dan tari istana lainnya dapat dipelajari oleh masyarakat luas.
Secara umum penari Srimpi mengenakan busana dan riasan seperti yang dipakai oleh pengantin putri pada upacara pernikahan. Busana yang dikenakan adalah dodot ageng dengan kain bermotif cindhe. Sedangkan untuk riasan menggunakan model paes ageng serta sanggul bokor mengkurep.
Pada masa lalu, Srimpi pernah dibawakan oleh penari kakung (pria). Penari Srimpi kakung tersebut menggunakan busana rompen (baju tanpa lengan), gelung sinyong, dan jamang (hiasan kepala) dengan bulu burung onta atau bulu burung kasuari. Srimpi kakung ditiadakan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, busana dan riasan Srimpi kakung kemudian beralih diterapkan pada penari putri.
Terdapat beberapa jenis senjata yang selalu melengkapi penampilan penari Srimpi, seperti keris, panah, jebeng, maupun pistol. Keris digunakan pada Srimpi Muncar, Jebeng pada Srimpi Jebeng, sedangkan pistol diterapkan pada Srimpi Merak Kesimpir, Srimpi Pandhelori dan Srimpi Pramugari.
Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1940-1988) terjadi penyederhanaan besar-besaran pada berbagai hal di Keraton Yogyakarta, termasuk dalam seni pertunjukan. Tari Srimpi yang dahulunya digelar dengan durasi waktu mencapai empat jam dipadatkan hingga kurang dari satu jam.
Pertunjukan tari Srimpi pada masa kini telah mengalami pergeseran fungsi, yang semula cenderung berfungsi sebagai ritual kini kadang beralih menjadi pertunjukkan. Namun dalam lingkup tembok keraton dan para pelestari tradisi, Srimpi sebagai tari sakral tetap lestari. Nilai-nilai luhur yang dikandung dalam tarian tersebut terus hidup, menghidupi jiwa budaya Jawa.