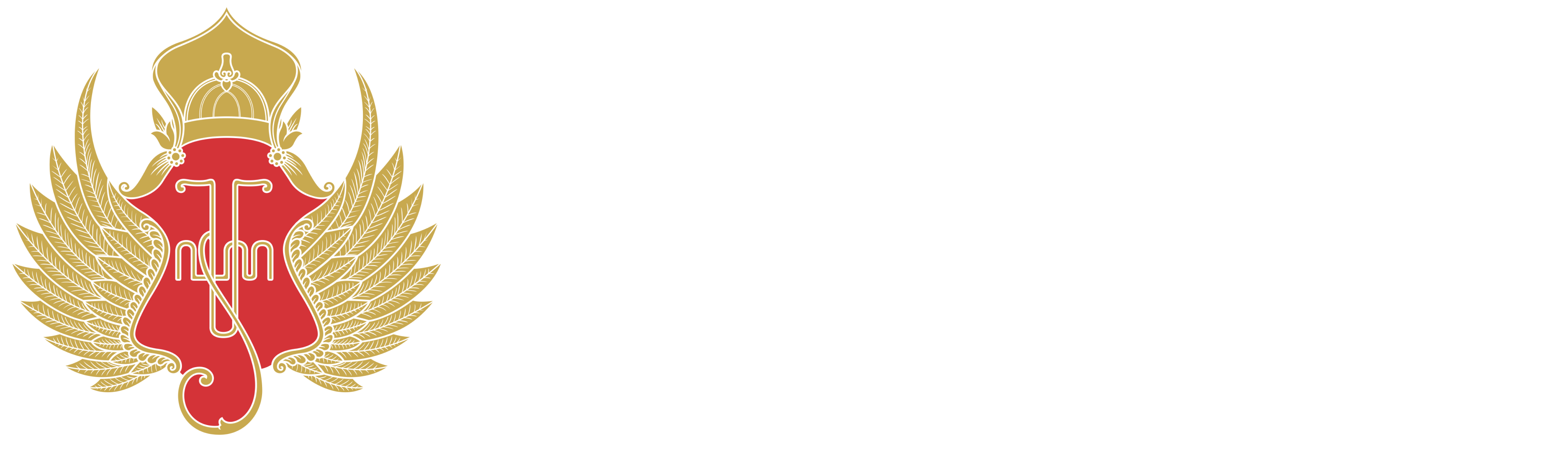Pada tanggal 3 Maret 1880, lahirlah putra Sri Sultan Hamengku Buwono VII dari rahim Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang diberi nama Gusti Raden Mas (GRM) Sujadi. Setelah dewasa GRM Sujadi bergelar Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo yang kelak dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.
Perjalanan GPH. Puruboyo sebagai penerus tahta Kasultanan Ngayogyakarta sesungguhnya melalui jalan yang panjang. Awalnya, Sri Sultan Hamengku Buwono VII telah mengangkat putra sulung GKR Hemas, GRM Akhadiyat, sebagai putera mahkota. Akan tetapi, tidak lama setelah dinobatkan sebagai putera mahkota, GRM Akhadiyat sakit hingga meninggal dunia. Sri Sultan Hamengku Buwono VII kemudian mengangkat GRM Pratistha sebagai pengganti putera mahkota sebelumnya. Putera mahkota kedua yang juga bergelar Adipati Juminah ini di kemudian hari gelarnya dicabut karena alasan kesehatan. Posisi putera mahkota untuk yang ketiga kali kemudian jatuh kepada GRM Putro. Nasib baik tidak berpihak kepada GRM Putro yang juga meninggal dunia akibat sakit keras. Akhirnya, pilihan Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk didudukkan sebagai mahkota jatuh kepada GPH Puruboyo.
Tahun 1920 GPH. Puruboyo sedang menempuh studi di Belanda, ketika sang ayahanda Sri Sultan Hamengku Buwono VII mengungkapkan niat untuk lengser keprabon. Mendengar hal ini, Residen Jonquire yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta, mengusulkan kepada Gubernur Jendral van Limburg Stirum agar upaya pergantian tahta dipercepat.
Dikarenakan posisi GPH. Puruboyo masih di Belanda, maka van Limburg Stirum yang menyetujui gagasan tadi memerintahkan Jonquire agar mendesak Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk segera memanggil pulang GPH Puruboyo melalui telegram. Sri Sultan Hamengku Buwono VII menyetujui usulan tersebut dan mengirimkan telegram pada awal November 1920. Di dalam telegram itu Sri Sultan Hamengku Buwono VII menyampaikan agar Gusti Puruboyo jangan terlalu lama di Eropa karena para putera dan puteri, kerabat dan abdi dalem sudah menanti-nanti kepulangan beliau.
Setelah GPH Puruboyo setuju untuk pulang ke Yogyakarta dan dijadikan pengganti ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono VII memutuskan untuk lereh keprabon (turun tahta) dan beristirahat di Pesanggrahan Ambarukmo. Pada tanggal 8 Februari 1921, GPH Puruboyo kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.
Prinsip Raja
Kekayaan keraton yang cukup besar kala itu, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII untuk mendorong dunia pendidikan. Seperti ayahandanya, beliau juga mengharuskan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan formal setinggi mungkin, bahkan bila perlu hingga ke Negeri Belanda.
Sekolah-sekolah, organisasi dan munculnya aktivis banyak berkembang di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII . Sekolah Taman Siswa Nasional (berdiri 3 Juli 1922), Organisasi Politik Katholik Jawi (1923) dan Kongres Perempuan (1929) adalah contoh-contohnya.
Perhatian beliau di dunia kesehatan juga sangat besar, misalnya dengan mendukung pengadaan ambulans untuk Rumah Sakit Onder de Bogen (saat ini: Panti Rapih).
Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga banyak mengadakan perombakan/rehabilitasi bangunan. Bangsal Pagelaran, Tratag Siti Hinggil, Gerbang Danapratapa dan Masjid Gede adalah beberapa bangunan yang beliau perbaiki.
Di dalam lingkungan keluarganya sendiri, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga banyak melakukan terobosan. Hal tersebut terjadi bahkan semenjak sebelum menjadi Sultan. Salah satunya adalah dengan “menitipkan” anak-anaknya di luar lingkungan keraton. BRM Dorodjatun, yang kelak menjabat sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dari umur 4 tahun sudah dititipkan ke keluarga Belanda. Tidak ada inang atau pengasuh yang menjaga. Pangeran kecil itu dituntut untuk hidup mandiri dan merasakan hidup sebagaimana kebanyakan masyarakat pada umumnya.
Langkah-langkah yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII tersebut adalah cerminan dari sikap beliau yang berpedoman pada ungkapan “wong sing kalingan suka, ilang prayitane”, orang yang sudah merasakan nikmat akan hilang kewaspadaannya.
Pada tahun 1939, beliau memanggil putranya, BRM Dorodjatun yang sedang belajar di Negeri Belanda. Setelah keduanya bertemu di Batavia, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII kemudian menyerahkan pusaka keraton Kyai Joko Piturun kepada BRM Dorojatun. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa BRM Dorojatun telah ditunjuk menjadi penerus tahta sepeninggalnya.
Setibanya dari Batavia menjemput BRM Dorojatun tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII wafat pada tanggal 22 Oktober 1939 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dimakamkan di Astana Saptarengga, Pajimatan Imogiri.
Peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII
Seperti sudah disinggung di atas, di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Yogyakarta mengalami kemajuan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang arsitektur, bentuk fisik kraton saat ini adalah hasil perombakan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.
Di bidang seni tari, banyak sekali tarian diciptakan pada era kepemimpinan beliau. Diantaranya adalah Beksan Srimpi Layu-layu, Beksan Gathutkaca-Suteja, Bedaya Gandrung Manis, Bedaya Kuwung-Kuwung dan masih banyak lagi. Pada masa ini pula, pembakuan terhadap pakem tari klasik Gaya Yogyakarta dimulai.
Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII juga dikenal sebagai masa keemasan pentas wayang wong. Pementasan wayang orang besar-besaran hingga memakan waktu tiga hari banyak dan sering dilakukan di era ini. Lebih dari 20 lakon dikembangkan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.
Dari segi busana untuk Tari Bedaya, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII melakukan perubahan besar. Karya Tari Bedaya yang lahir pada era ini tidak menggunakan kampuh dan paes ageng. Di masa ini penari menggunakan jamang dan bulu-bulu, baju tanpa lengan serta kain seredan.